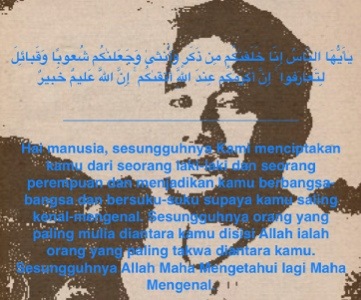“Terima kasih tuhan, saya masih bisa ngetawain presiden dan anak presiden untuk 5 tahun ke depan.”
Itulah respons salah seorang netizen atastweet kocak Kaesang Pangareb beberapa waktu lalu. Putra bungsu Presiden Jokowi itu me-retweet foto yang diunggah oleh akun bapaknya yang tengah berpose dengan sejumlah perempuan pemimpin dari negara-negara G20 di sela konferensi di Osaka, akhir Juli lalu. Bunyi caption foto itu: di antara perempuan-perempuan perkasa. Kaesang me-retweet dengan menambahkan: cc: ibu.
Menjadi orang yang lucu itu tidak gampang. Jumlah orang lucu di dunia ini, jika dikumpulkan, barangkali akan menjadi “kaum minoritas”. Tapi, layaknya sebagian “kaum minoritas” lainnya, mereka memberi warna yang berbeda pada dunia dan kehidupan. Orang-orang yang lucu biasanya tampil apa adanya, tidak “jaim”, dan mampu menghidupkan suasana di sekitarnya.
Orang yang lucu, atau bahasa kerennya memiliki “sense of humor” yang tinggi tidak mudah marah, menyikapi hidup dengan santai, cenderung memandang segala sesuatu dengan cara yang positif. Mereka tidak membenci orang lain, tidak menyebar hoaks dan berita bohong, serta tidak mencaci, menghujat, dan berkata kasar. Jika mereka mengkritik, atau mengungkapkan suatu keberatan dan ketidaksetujuan, biasanya disampaikan tidak dengan nada “nyinyir”, melainkan dengan satire –sinis, tapi tidak menyinggung, dan tetap mengundang tawa.
Orang lucu ada di sekitar kita, namun sekali lagi tidak banyak. Dalam satu lingkaran pergaulan misalnya, biasanya hanya ada satu orang lucu, yang menjadi pusat perhatian, membuat kebersamaan menjadi menyenangkan –bahasa iklannya:nggak ada lo nggak rame. Mereka memicu gelak tawa, membahagiakan orang lain, kadang sampai level “pengorbanan” dengan mentertawakan diri mereka sendiri, untuk membuat orang lain mendapatkan semacam “pencerahan” batin.
Kita pernah memiliki presiden seorang kiai yang sangat lucu. Cerita-cerita lucunya menjadi kisah abadi yang dikenang oleh orang-orang sekitar atau yang pernah berada di dekatnya, dan dikisahkan kembali kepada orang lain, sehingga menjadi “cerita rakyat” yang dikenal luas. Dia adalah Kiai Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Salah satu kelucuannya yang setiap kali diulang tetap membuat orang tertawa adalah “celetukannya” tentang bagaimana dirinya bisa menjadi presiden.
“Saya menjadi presiden cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amien Rais.” Bagi yang mengalami zaman itu, atau setidaknya membaca sejarah politik pada masa itu, tentu paham betul apa yang dimaksud Gus Dur tersebut. Orang-orang dengan tingkat kelucuan seperti Gus Dur itu kadang (atau sering) membuat orang lain iri, karena dengan kelucuannya dia mampu mengungkapkan sebuah pemikiran, ide, gagasan, atau pendapat yang sebenarnya sangat kompleks dan serius, dengan cara yang ringan, menghibur, dan membuat orang tertawa.
Jika ia seorang penulis, orang yang lucu akan menjadi penulis yang jempolan. Lagi-lagi tidak banyak, tapi kita punya Mahbub Djunaidi dan Emha Ainun Nadjib, penulis yang sangat lucu. Gus Dur sendiri juga pernah aktif menulis di media massa, tapi tulisan-tulisannya memang tidak selucu ketika dia berkisah secara langsung. Emha Ainun Nadjib bicara di forum-forum pengajian dan pidato-pidato sama lucunya dengan tulisan-tulisannya. Sedangkan Mahbub Djunaidi, dari kisah-kisah yang dituturkan oleh orang-orang yang mengenalnya, dalam keseharian juga selucu tulisan-tulisannya.
Di era belakangan, kita mengenal orang-orang yang lucu dalam menulis dan berbicara lewat sosok-sosok seperti Raditya Dika dan Ernest Prakasa. Mereka adalah para penulis lucu yang pilih tanding, sekaligus juga para “comic“, stand up comedian“, yang digemari jutaan anak muda, dan menginspirasi lahirnya generasi baru orang-orang lucu. Lebih belakangan lagi, keduanya terjun ke dunia film, menjadi sutradara dan aktor, dan melahirkan film-film yang juga lucu dan sangat menghibur.
Yang barangkali jarang terpikirkan adalah bahwa humor, kelucuan, dan orang-orang yang lucu tidak hanya dibutuhkan sebagai hiburan. Dalam membangun dan mengelola negara yang demokratis, sosok, sikap, dan sifat seperti itu juga diperlukan. Lagi-lagi zaman sudah membuktikan. Gus Dur yang lucu itu adalah sosok penganjur dan pejuang demokrasi sejak awalnya –bersama-sama sejumlah tokoh lainnya ia membentuk Forum Demokrasi yang kritis pada pemerintahan otoriter Soeharto yang kala itu sedang kuat-kuatnya dan jaya-jayanya.
Demokrasi tidak bisa diwujudkan tanpa orang-orang yang lucu. Selama 32 tahun era Orde Baru dulu, negara ini dipimpin oleh seorang presiden, seorang jenderal yang selalu tersenyum dan terlihat hangat-kebapakan –sampai-sampai dijuluki “the smiling general“. Tapi, ia sama sekali bukan orang yang lucu, sebaliknya ia memimpin dengan membungkam suara rakyat, memberangus kebebasan warga, dan menangkapi orang-orang yang mengkritiknya.
Jokowi dan keluarganya, terutama putra-putranya adalah orang-orang yang lucu. Ini bisa kita saksikan langsung dari interaksi mereka di media sosial yang begitu terbuka, apa adanya –mereka bisa saling ledek seolah-olah sedang “bermusuhan”. Itulah lucu gaya Jawa-Solo. Kaesang misalnya, mencitrakan diri sebagai “anak yang tidak diakui”. Dan, hubungannya dengan Gibran, kakaknya, seolah-olah tidak pernah rukun. Ketika sang kakak mempromosikan bisnisnya misalnya, Kaesang akan menyahut: Ini punyanya Mas Gibran? Emoh!”
Ungkapan netizen di atas, yang diformulasikan dalam kalimat sederhana, mensyukuri keadaan di mana dirinya masih bisa menertawakan presiden dan anak presiden untuk lima tahun ke depan, sebenarnya menggambarkan politik kita saat ini, dan akan seperti apa negeri ini dikelola ke depannya. “Ngetawain presiden dan anak presiden” adalah aspek yang barangkali selama ini luput dari analisis para pengamat dan pakar politik, ketika membicarakan tentang demokrasi.
Untuk membangun demokrasi, kita perlu banyak tertawa, tapi bukan menghina, apalagi mengulang-ulang hinaan yang itu-itu saja, misalnya tentang logat bahasa Inggris presiden. Tentu saja, dengan menampilkan diri sebagai sosok-sosok yang lucu, Presiden Jokowi dan keluarganya tidak serta merta lantas “kebal” kritik. Namun, dalam masyarakat yang berlimpah kebebasan seperti sekarang ini, membedakan antara kritik dan hinaan kerap menjadi tantangan yang berat.
Kita memang patut bersyukur, bahwa dalam gempuran berbagai hinaan, ujaran kebencian, berita bohong, bahkan fitnah yang tak pernah putus, putra-putra presiden Jokowi tidak pernah kehabisan kesabaran, dan kehilangan “sense of humor” mereka. Mereka tetap melucu, saling ledek, kadang menertawakan diri mereka sendiri. Demokrasi memang memerlukan pengorbanan dan harga yang mahal, dan mereka telah memenuhi dan membayarnya dengan merelakan diri menjadi objek tertawaan.